Wisata
Asyiknya Wedangan Ala Kutho Solo
Published
7 tahun agoon
1881 ViewsKisah bermula dari hadirnya listrik di Surakarta pada tahun 1902. Sinar lampu menerangi tubuh kota, geliat kehidupan malam pun menunjukkan tanda-tandanya. Pertunjukan layar tancap di alun-alun, bioskop di taman Kebonrojo alias Sriwedari, pertemuan plus acara bersuka ria di gedung Abipraya Singosaren dan Societiet Harmony (timur Benteng Vastenburg) ialah potret historis dampak yang dituai kota setelah listrik menyala dan lampu mengguyurkan sinarnya. Pekerjaan siang hari dapat dilembur kendati malam larut. Sang malam bukan lagi waktu jeda bagi para pekerja dan penikmat hiburan kota.
Fenomena kota berdenyut usai magrib hingga malam menua, terbaca oleh kaum marginal yang kepincut mengadu nasib ke Kutha Sala, tempat raja bercokol. Periode itu, Surakarta disebut kota urbanisasi layaknya Jakarta yang laris jadi jujugan perantau mengais secentong nasi. Hanya saja, Solo tampak unik lantaran model urbanisasinya varian. Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran menawarkan jenis urbanisasi tradisional, membuka lowongan abdi dalem lewat proses magang. Kemudian, institusi pemerintah Belanda mempengaruhi jenis urbanisasi kolonial, mengiming-imingi keluarga priyayi menjadi pegawai birokrasi profesional asalkan mengenyam bangku sekolah Eropa. Yang terakhir, perusahaan industri batik, pertokoan Tionghoa serta pasar tradisional mencuri perhatian kelas bawah untuk mendaftarkan diri sebagai buruh, sehingga terciptalah model urbanisasi modern di sektor informal.
Peluang mengais rejeki yang bertebaran di waktu malam, ditubruk oleh wong cilik, kelas yang kurang beruntung di dunia pendidikan dan tak berjejaring dengan kelompok bangsawan. Mereka rata-rata berasal dari pinggiran Surakarta khususnya Klaten, mencoba peruntungan dengan menjajakan makanan ringan. Melayani kebutuhan perut penghuni kota yang melilit sepulang menikmati pertunjukan tengah malam. Atau, sekadar melayani masyarakat yang gemar nglayab di malam hari. Mereka tak perlu keahlian (karena memang tiada kesempatan duduk di bangku sekolah), cuma bermodal duit secukupnya serta tenaga.
Makanan tidak ditaruh di gerobak lalu didorong seperti sekarang, waktu itu hik masih dipikul. Untuk menjaring pembeli sebanyak mungkin, bakul hik berhenti di titik-titik keramaian macam taman Sriwedari dan Pasar Pon. Dalam atlas sejarah kesenian Kota Solo, dua lokasi tersebut merupakan arena hiburan yang tidak pernah sepi pengunjung. Memilih manggrok atau menetap di saban ujung gang seperti kebanyakan penjual hik dewasa ini, sama artinya “bunuh diri,” kesepian yang bakal diperoleh.
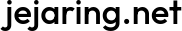

Chords, Sultan – Berpisah Di ujung Jalan (Cover By...

Chords, Arief – Satu Rasa Cinta (Cover By Gita KDI)

Chords, Ikan Dalam Kolam (Versi Campursari Dike Sabrina)

Chords, Gilga Sahid- Nemu(Cover By Difarina Indra)






