Wisata
Asyiknya Wedangan Ala Kutho Solo
Published
7 tahun agoon
1878 ViewsAktivitas ekonomi terus berdetak dan ruang kota tak pernah lengang, adalah berkat keberadaan hik yang mulai buka sore dan tutup hingga hari bersalin pagi. Maka, Solo sejak itu ditemploki gelar “kota yang tak pernah tidur,” baik penghuni maupun ekonominya. Fenomena hik sanggup bertahan seabad lebih lantaran ia tidak mengenal kasta sosial, juga merangkul lintas umur. Konsumennya beragam. Mereka yang berkalung sarung dan bersandal butut bakal dilayani dengan muka ramah. Mereka bercaping dan keringatnya ber-ler-leran habis narik becak, juga tak akan malu memesan secangkir wedang teh. Beda soal dengan restoran atau warung makan, pembeli dengan ciri-ciri tadi akan dilirik aneh. Model masyarakat-paguyuban mudah ditemukan di arena hik, meski kita memasuki era modern yang masyarakatnya cenderung berperilaku individualis.
Soal dagangan, hik tempo dulu lebih komplet dibandingkan kini. Umar Kayam, budayawan yang besar di Solo, melukiskan bahwa hik menjual nasi langgi yang bungkusannya masih lebih konkret, gemuk, padat, dan berisi lauk-pauk yang tak kalah konkretnya. Tokoh berjuluk “si lidah cerdas” dan pencetus istilah “makyus” pertama kali ini, mengatakan bahwa saat itu belum ada nasi kucing yang jadi ikon angkringan era sekarang. Itulah salah satu makanan yang sukar ditemukan pada hik. Ikan wader berukuran besar-kecil dan yuyu (kepiting) sawah tergolek di hik. Makanan jenis itu, tahun 1940-an, dihargai dalam sen-senan rupiah. Biarpun murah, tubuh wader-wader ini mlenus-mlenus (gemuk), lumayan untuk pengganjal perut barang sebentar. Gorengan yang disajikan meliputi pisang goreng, limpung, blanggreng dan kita dapat menikmatinya cukup dengan merogoh kocek sakbil alias setengah sen. Apiknya, sampai detik ini, hik masih pantas disebut sebagai katup pengaman bagi kelompok berkantong cekak.
Yang sulit bersalin dari hik adalah fungsi sosialnya. Hik menjelma menjadi tempat ngobrol tentang segala aspek kehidupan. Umar Kayam kembali menegaskan bahwa kalau mau kulak warta dan mendengarkan orang Solo berspekulasi tentang makna kehidupannya, di hik itulah pantasnya. Para abang becak, pekerja bangunan, pengangguran, dengan sisa-sisa uang mereka, pasti akan singgah di hik untuk jajan sepotong gorengan atau sebungkus dua bungkus nasi. Setelah hik berhenti dipikul keliling, manggrok di pinggir jalan, ada tempat duduk berupa dingklik panjang. Jajanan yang ditawarkan dan paras penjaja asyik ngobrol diterangi lampu senthir yang kilaunya kurang terang. Hidup guyonan yang masuk akal bahwa wedangan berlampu kencar-kencar (terang sekali) siaplah kukut atau sepi pengunjung, sebab orang Solo senang glenak-glenik dalam keremangan.
Satu pencapaian hebat ialah konsep hik kini diadopsi para pemodal. Ia ditaruh di dalam rumah, tidak lagi bergerobak di bibir jalan. Dilirik dan diyakini menjadi lahan menggiurkan untuk menjaring pembeli kelas menengah ke atas. Seketika, pernyataan angkringan merupakan stereotif kaum marginal berkantung cekak, rontok. Buruh dan abang becak berpikir belasan kali bila berhasrat masuk di lingkungan ini. Meski demikian, fakta tersebut menunjukkan bahwa hik sebagai model wirausaha wong cilik, rupanya ditiru oleh kelompok kelas menengah. Mereka bolehlah bangga atas kenyataan itu.
Begitulah asal-usul hik di Solo yang seabad lebih berhasil mewadahi interaksi sosial warga. Dia juga menjadi juru selamat atau tumpuan masyarakat bawah. Menjamurnya hik menimbulkan kesan pula, warga Solo senang keluyuran dan ngobrol ngalur ngidul sampai larut. Tak harus risau kelaparan manakala keluyuran menikmati sore hingga larut malam di Kota Bengawan. Sekali lagi, hik, kehidupan malam, dan Solo ialah sebuah untaian sejarah yang tak bisa dipenggal.
Sumber Video: Terasolo; Sumber Artikel: Joglosemar.co
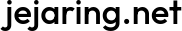

Chords, Sultan – Berpisah Di ujung Jalan (Cover By...

Chords, Arief – Satu Rasa Cinta (Cover By Gita KDI)

Chords, Ikan Dalam Kolam (Versi Campursari Dike Sabrina)

Chords, Gilga Sahid- Nemu(Cover By Difarina Indra)






